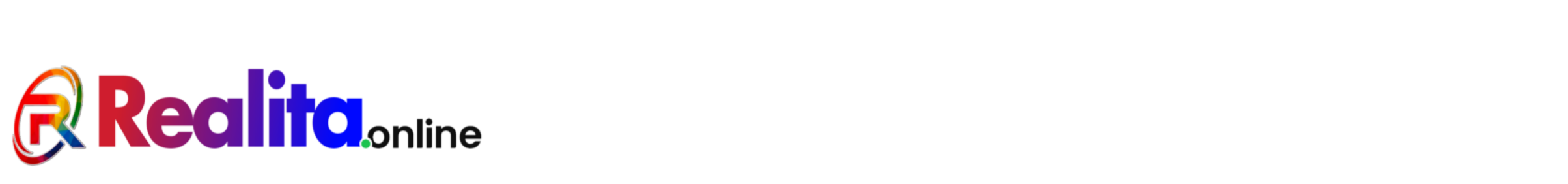Realita.online
“Saya harus pilih antara bayar listrik atau bayar SPP anak. Dan listrik lebih dibutuhkan sekarang,” ujar Nani (38), ibu rumah tangga di Bekasi, saat ditanya alasan anaknya berhenti sekolah.
Di tengah gegap gempita digitalisasi pendidikan dan wacana ‘merdeka belajar’, ada cerita lain yang berjalan diam-diam: gelombang anak putus sekolah dari lembaga pendidikan swasta kecil. Fenomena ini nyaris tak terdengar, karena bukan sekolah negeri yang menjadi perhatian pemerintah, dan bukan pula sekolah elite yang memiliki donatur tetap.
Sekolah-sekolah swasta non-elite, seringkali berdiri di gang sempit kota pinggiran atau desa terpencil, menjadi satu-satunya opsi pendidikan formal bagi anak-anak dari keluarga yang tak memenuhi syarat masuk sekolah negeri, entah karena domisili atau nilai.
Badai Diam :
Ketika Satu Siswa Mundur, Lima Lainnya Mengikuti
Di salah satu sekolah swasta kecil di Depok, jumlah siswa kelas IX berkurang dari 21 menjadi hanya 13 dalam waktu tiga bulan. Kepala sekolah, Ibu Lina, menyebutnya sebagai “efek domino ekonomi.”
“Awalnya satu anak berhenti karena orang tuanya kehilangan pekerjaan. Tak lama, beberapa orang tua lain minta izin untuk menunggak bayaran. Tapi akhirnya memilih mengundurkan diri karena malu,” ujar Lina.
Sebagian siswa memang berpindah ke sekolah negeri. Tapi lebih banyak yang justru berhenti total dari sistem pendidikan, memilih membantu orang tua, atau bekerja serabutan di usia 14-15 tahun.
Sekolah Tanpa Anggaran, Siswa Tanpa Arah
Sekolah swasta kecil tak mendapat subsidi BOSDA maupun BOSNAS yang setara dengan sekolah negeri. Padahal, mereka tetap harus membayar gaji guru, biaya listrik, ATK, dan operasional. Di sisi lain, mereka juga diminta memenuhi standar kurikulum nasional.
Guru-guru di sekolah ini sering kali hanya dibayar Rp500.000-Rp800.000 per bulan. Tidak sedikit dari mereka yang tetap bertahan karena “kasihan anak-anak.”
Data yang Tak Terdeteksi
Menurut BPS (data hingga 2023), angka putus sekolah di Indonesia secara nasional menunjukkan penurunan. Tapi ini tak merepresentasikan realitas sekolah swasta kecil.
Lembaga seperti SMERU Research Institute mencatat bahwa data anak putus sekolah swasta jarang sekali terpetakan karena tidak masuk sistem Dapodik atau tidak dilaporkan secara aktif.
“Kami seperti zona abu-abu dalam sistem pendidikan,” kata seorang pengelola yayasan sekolah swasta di Karawang.
Realitas Anak : “Saya Mau Sekolah, Tapi Tidak Bisa Bantu Makan di Rumah”
Wati (15), anak dari keluarga buruh cuci, pernah menjadi juara kelas. Ia akhirnya berhenti sekolah saat masuk kelas VIII.
“Saya malu kalau tiap bulan disuruh bawa uang SPP. Guru saya baik, tapi saya tahu sekolah butuh uang juga,” katanya lirih.
Kini, Wati bekerja membantu ibunya mencuci pakaian di rumah-rumah warga. Ia masih menyimpan buku pelajaran, berharap bisa belajar sendiri di waktu senggang.
Siapa yang Peduli?
Dimana Negara?
Sayangnya, tak banyak LSM atau donatur yang menyasar sekolah swasta kecil karena tidak dianggap “darurat” seperti anak jalanan atau anak korban bencana. Pemerintah daerah pun lebih fokus pada capaian angka partisipasi di sekolah negeri.
Beberapa inisiatif lokal mulai muncul. Di Bogor, misalnya, sekelompok relawan membuat program “Adopsi SPP”—di mana warga atau donatur bisa menanggung biaya satu anak di sekolah swasta tertentu selama setahun.
Solusi Bukan Sekadar Uang:
Menurut Dr. Ratna Amalia, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, solusi anak putus sekolah bukan hanya pembebasan biaya.
“Sekolah harus didampingi membangun ekosistem ramah siswa miskin. Mulai dari fleksibilitas pembayaran, pendekatan psikologis kepada orang tua, hingga pembelajaran berbasis praktik untuk anak-anak yang bekerja.”
Penutup :
Sebuah Tanya yang Menggema
Di negeri ini, ribuan anak seperti Wati mungkin sedang duduk di beranda rumah, memandangi seragam sekolah yang tak akan mereka pakai lagi.
Bukan karena mereka bodoh. Tapi karena mereka miskin.
Apakah pendidikan masih hak semua warga negara, atau hanya untuk yang mampu membayar ?
Angka Cepat :
– Jumlah sekolah swasta non-elite di Jabodetabek : ±1.200
– Rata-rata siswa aktif/survive di kelas akhir : <70%
– Rata-rata tunggakan SPP siswa : Rp 150.000–Rp 500.000/bulan